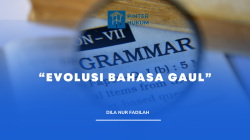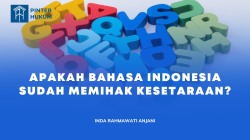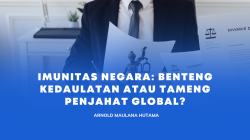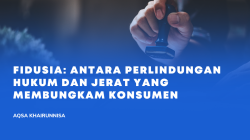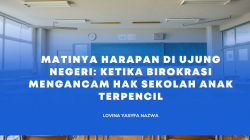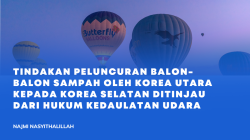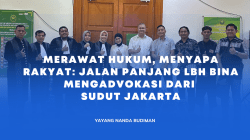Pendahuluan
Perbincangan mengenai keadilan dalam praktik hukum Indonesia kerap bertemu pada satu simpul persoalan: kecenderungan hukum berjalan sebagai perangkat formal belaka. Aturan tertulis memang menyusun fondasi bagi setiap sistem hukum, tetapi ketika formalisme menjadi orientasi utama, hukum tampak seperti bangunan kokoh yang kehilangan penghuni, hidup tanpa sensitivitas sosial, dan terasa jauh dari kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tampak “tanpa jiwa”, seolah bekerja atas mekanisme prosedural yang steril dari realitas kemanusiaan.
Kondisi demikian menandai kesenjangan antara law in books dan law in action, sebuah perbedaan yang sejak lama dikritik oleh para pemikir hukum progresif. Roscoe Pound pernah menegaskan, “Law must be stable, yet it cannot stand still.” Pemikiran itu membuka ruang untuk menilai praktik hukum Indonesia yang kerap terpaku pada kepastian, tetapi kurang memberi ruang bagi keadilan substantif.
Dalam praktiknya, formalisme hukum kerap melahirkan putusan yang sah secara prosedural tetapi gagal menangkap denyut persoalan yang melingkupinya. Ketika hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lebih terpaku pada teks ketimbang konteks, hukum perlahan menjauh dari fungsi dasarnya: menata kehidupan sosial dengan mempertimbangkan kompleksitas manusia yang ada di dalamnya. Akibatnya, keadilan terasa seperti konsep abstrak yang berdiri di menara gading, sementara masyarakat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kebenaran formal belum tentu selaras dengan kebenaran hidup sehari-hari.
Kritik terhadap formalisme ini bukanlah ajakan untuk meninggalkan aturan tertulis, melainkan seruan untuk menempatkannya dalam kerangka pemaknaan yang lebih luas. Hukum seyogianya tidak hanya dibaca melalui kacamata positivistik yang memisahkan aturan dan moralitas secara kaku. Dalam banyak kasus, kepekaan moral dan pertimbangan sosiologis justru menjadi faktor penentu apakah suatu putusan mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan, bukan sekadar keadilan yang dinyatakan. Di sinilah relevansi pendekatan realisme hukum dan mazhab pemikiran kritis, yang melihat hukum sebagai institusi yang tidak pernah berdiri di ruang hampa.
Baca Juga: Resensi Buku: Antropologi Hukum Indonesia
Indonesia sendiri memiliki dinamika sosial yang begitu beragam, sehingga pendekatan hukum yang terlalu mekanistis sering kali gagal menangkap keunikan persoalan yang muncul. Ketika hukum hanya berputar pada nalar standar, ia tidak mampu menembus lapisan-lapisan ketidakadilan struktural yang mengakar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum yang “tanpa jiwa” bukan sekadar metafora, melainkan refleksi dari kegagalan sistem untuk mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi pusat dari setiap praktik penegakan hukum.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai keadilan tidak dapat berhenti pada upaya menafsirkan aturan secara literal. Diperlukan keberanian untuk melihat hukum sebagai proses yang hidup—yang tumbuh, menyesuaikan diri, dan merespons kompleksitas zaman. Hukum yang berjiwa bukanlah hukum yang meninggalkan kepastian, melainkan hukum yang mampu menggabungkan kepastian dan kemanfaatan, serta menjadikan kemanusiaan sebagai landasan utamanya. Dari sinilah reformasi pemikiran dan praktik hukum di Indonesia harus dimulai: dengan menghidupkan kembali jiwa dalam hukum, agar ia benar-benar hadir bagi masyarakat yang dilayaninya.
Formalisme dalam Sistem Hukum Indonesia
Formalisme dalam praktik hukum Indonesia tercermin dari kecenderungan aparat penegak hukum menempatkan aturan tertulis sebagai sumber kebenaran tunggal. Proses hukum bergerak mengikuti simpul-simpul administratif, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Pola tersebut tampak dari banyak perkara yang menonjolkan legalitas dibandingkan penilaian atas situasi konkret.
Fenomena ini muncul misalnya pada perkara-perkara pelanggaran kecil yang melibatkan masyarakat rentan. Putusan dan langkah hukum sering kali menitikberatkan pada pasal dan mekanisme prosedural, tanpa mempertimbangkan ketimpangan sosial yang melatarbelakanginya. Komisi Yudisial dalam beberapa laporan tahunan mencatat adanya kekhawatiran publik terhadap pola putusan yang “kurang responsif” terhadap kondisi masyarakat kecil, terutama dalam perkara pidana ringan dan sengketa tanah.
Penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan corak yang konservatif. Argumen hukum dibangun melalui pembacaan literal terhadap norma yuridis, sementara interpretasi kontekstual kerap tersingkir. Padahal, banyak persoalan hukum di Indonesia berakar pada dinamika sosial yang tidak tercakup secara eksplisit dalam aturan.
Baca Juga: Hukum Positif Indonesia dalam Teori “ Hukum Merupakan Kehendak Etis Umum “ Dari J.J.Rousseau.
Pandangan Oliver Wendell Holmes Jr. dalam tradisi legal realism relevan di sini: “The life of the law has not been logic; it has been experience.” Kutipan tersebut menegaskan bahwa hukum yang hanya mengandalkan nalar tekstual akan kehilangan keterhubungan dengan realitas sosial yang terus berubah.
Ketika Keadilan Substantif Menjadi Korban
Salah satu konsekuensi formalisme ialah terciptanya kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan. Tidak sedikit perkara yang memperlihatkan bagaimana mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya lebih besar dapat mengarahkan proses hukum sesuai kepentingannya, sementara masyarakat kecil terjebak dalam belantara prosedur yang tidak mereka pahami.
Kasus-kasus kriminalisasi masyarakat adat, terutama terkait sengketa lahan, menunjukkan bagaimana dokumen formal dan sertifikat menjadi alat tunggal penentu legalitas, sementara sejarah penguasaan tanah dan kehidupan komunal yang sudah berlangsung turun-temurun kurang mendapat tempat sebagai pertimbangan hukum.
Ketika logika formalisme mengambil alih ruang pertimbangan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak hidup masyarakat adat kerap berujung pada putusan yang tidak mencerminkan pengalaman sosial mereka. Dalam banyak sengketa, struktur hukum menempatkan sertifikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan yang sah, padahal proses penguasaan tanah oleh komunitas adat sering kali berlangsung sebelum administrasi pertanahan modern terbentuk. Kondisi ini menciptakan ruang kosong yang menelan jejak sejarah komunal, sehingga suara masyarakat adat tidak memperoleh bobot yang sepadan dalam ruang persidangan.
Fakta bahwa 241 konflik agraria terjadi sepanjang 2023 menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bagaimana problem legal-formal masih berulang. Sebagian besar konflik tersebut melibatkan masyarakat adat atau petani lokal yang berhadapan dengan korporasi besar, dan proses hukum kerap memberikan keunggulan kepada pihak yang mampu menunjukkan dokumen resmi. Fenomena ini mempertegas bahwa formalisme tidak sekadar persoalan teknis, tetapi turut mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam arena hukum.
Ketimpangan semakin tampak ketika proses hukum memasuki tahap pembuktian. Pengadilan sering memusatkan perhatian pada dokumen tertulis sebagai bukti utama, sementara bukti-bukti sosial seperti kesaksian tokoh adat, peta partisipatif, atau rekam jejak pemanfaatan lahan dianggap kurang memiliki kekuatan pembuktian. Cara pandang seperti ini membuat masyarakat adat berdiri di ruang pengadilan tanpa modal yang setara. Posisi mereka bukan sekadar lemah secara ekonomi, tetapi juga lemah secara epistemik karena pengalaman mereka tidak diterjemahkan ke dalam bahasa hukum yang dominan.
Dalam konteks ini, formalisme hukum menjadi semacam filter yang menentukan mana realitas sosial yang diakui dan mana yang diabaikan. Realitas yang tercatat secara administratif memperoleh legitimasi, sementara realitas yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat sering terpinggirkan. Akibatnya, banyak putusan yang tampak sah secara yuridis, tetapi menyisakan luka sosial yang dalam. Ketika proses hukum tidak mengakomodasi latar belakang historis, struktur adat, dan relasi sosial, keadilan substantif berada di posisi yang rapuh.
Pengalaman serupa terlihat pula dalam perkara-perkara pidana kecil. Banyak kasus pencurian skala rendah seperti pencurian buah atau barang kebutuhan sehari-hari yang berakhir dengan vonis penjara. Sementara itu, perkara korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar terkadang berujung pada hukuman yang relatif ringan. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa rata-rata hukuman koruptor pada 2022 berada pada kisaran dua tahun penjara, angka yang jauh dari berat jika dibandingkan dengan dampak sosial korupsi. Perbandingan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme yuridis dapat menghasilkan ketimpangan rasa keadilan di mata publik.
Dalam situasi semacam itu, formalisme tampak seperti jaring halus yang justru menangkap mereka yang berada di lapisan sosial paling bawah, sekaligus memberikan ruang gerak bagi mereka yang memiliki modal lebih besar. Pertimbangan moral, kepentingan sosial, dan konteks kehidupan masyarakat sering tidak mendapatkan tempat ketika aturan dibaca secara kaku. Padahal, setiap perkara membawa kompleksitasnya sendiri. Ketika kompleksitas tersebut diringkas menjadi sekadar pasal dan dokumen, hukum kehilangan kemampuannya untuk menyentuh inti persoalan kemanusiaan.
Lanskap ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif bukan gagasan abstrak yang menggantung di awan. Ia berkaitan langsung dengan keseharian masyarakat yang berhadapan dengan struktur hukum negara. Ketika praktik hukum lebih banyak menampilkan wajah yang formalistik, kelompok rentan berada pada posisi yang terus-menerus berhadapan dengan tembok yang tinggi. Pada titik inilah, kritik terhadap formalisme menemukan relevansinya. Kritik tersebut bukan sekadar menyoal metode penalaran hukum, tetapi menyangkut pertanyaan lebih besar: sejauh mana hukum mampu hadir sebagai ruang yang mendengarkan pengalaman manusia?
Perspektif Teoretis: Membaca Ulang Jiwa Hukum
Tradisi legal realism menempatkan pengalaman sosial sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari praktik hukum. Para realis mengkritik gagasan bahwa hukum dapat bekerja sepenuhnya melalui logika deduktif. Dalam konteks di negara kita, pendekatan ini menawarkan lensa untuk memahami bahwa praktik hukum memerlukan ketajaman membaca realitas, bukan hanya ketepatan menafsirkan teks.
Perspektif teoretis lain yang membuka ruang kritik terhadap formalisme ialah pendekatan sociological jurisprudence. Roscoe Pound memandang hukum sebagai “alat rekayasa sosial” yang bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut menyoroti bahwa hukum tidak berdiri sebagai menara gading yang terpisah dari dinamika hidup sosial. Pound menekankan bahwa efektivitas hukum terletak pada kemampuannya merespons kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini memperlihatkan relevansinya ketika melihat bagaimana berbagai aturan tertulis belum sepenuhnya selaras dengan persoalan struktural yang dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan sosial hingga kerentanan kelompok minoritas.
Sementara itu, arus pemikiran Critical Legal Studies (CLS) memberikan kritik lebih tajam dengan menyoroti bahwa hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan. Para pemikir CLS, seperti Duncan Kennedy, melihat bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, bahkan ketika tampak objektif dan rasional. Struktur hukum membawa bias kelas, ekonomi, dan politik yang bekerja secara halus dalam proses pengambilan keputusan. Ketika diterapkan dalam analisis terhadap praktik hukum Indonesia, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa hukum cenderung lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih besar, sementara masyarakat kecil sering berdiri di pinggiran proses hukum. Bias struktural semacam ini tampak dalam pola putusan, kesenjangan representasi hukum, hingga akses terhadap pendampingan yang memadai.
Perspektif lain dapat ditemukan dalam pemikiran Amartya Sen mengenai keadilan. Sen memandang keadilan sebagai pengalaman hidup yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata terpenuhi atau tidaknya kriteria normatif yang formal. Pandangan ini mendorong cara pandang yang lebih empiris terhadap persoalan hukum. Ketika diterapkan dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut mengingatkan bahwa keadilan tidak berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur pasal, melainkan terletak pada bagaimana keputusan hukum memberi dampak nyata bagi kehidupan manusia yang terlibat. Pendekatan Sen memberi makna pada pentingnya keadilan yang bersifat inklusif, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh struktur sosial dan birokrasi hukum.
Ketiga pendekatan teoretis ini legal realism, sociological jurisprudence, dan CLS memberikan kerangka yang saling melengkapi untuk membaca ulang jiwa hukum. Legal realism mengajak melihat pengalaman sosial, sociological jurisprudence menekankan relasi hukum dengan kebutuhan masyarakat, dan CLS membuka ruang kritik terhadap bias dalam struktur hukum itu sendiri. Ketiganya memperlihatkan bahwa hukum bukan sekadar teks, tetapi institusi yang bergerak di tengah masyarakat yang plural, dinamis, dan penuh ketegangan sosial.
Dalam konteks Indonesia, penggabungan ketiga pendekatan tersebut memberikan cara pandang yang lebih utuh terhadap persoalan yang muncul akibat formalisme. Ia menyingkap akar-akar struktural dari ketidakadilan, menjelaskan bagaimana aturan dapat menghasilkan dampak yang tidak seimbang, serta membantu membayangkan bentuk praktik hukum yang lebih responsif dan reflektif. Dengan demikian, pembacaan teoretis ini membuka ruang untuk menempatkan “jiwa hukum” sebagai orientasi fundamental dalam praktik penegakan hukum.
Jika hukum dipahami sebagai ruang dialog antara teks dan realitas, maka praktik hukum memperoleh peluang untuk bergerak lebih lentur dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pendekatan teoretis ini bukan sekadar menawarkan kritik, tetapi turut memberi fondasi bagi gagasan bahwa keadilan substantif dapat hidup berdampingan dengan kepastian hukum. Pada titik inilah, jiwa hukum menemukan relevansinya: ia tidak berada di luar aturan, tetapi hadir melalui cara aturan dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Membangun Pemahaman Baru tentang “Hukum yang Berjiwa”
Gagasan mengenai “hukum yang berjiwa” bukanlah konsep yang menolak keberadaan aturan formal. Justru sebaliknya, teks hukum tetap berfungsi sebagai peta, tetapi peta tidak pernah memiliki nilai bila tidak memahami medan yang dilaluinya. Jiwa hukum muncul ketika penegakan hukum menyentuh dimensi kemanusiaan, menimbang realitas sosial, dan menghadirkan rasa keadilan yang dapat dirasakan publik.
Dalam konteks Indonesia, banyak inisiatif reformasi hukum mulai mengarah pada pendekatan yang lebih responsif. Penguatan restorative justice dalam beberapa kebijakan, misalnya, menunjukkan adanya perubahan paradigma yang mencoba menghubungkan hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat. Perkembangan ini membuka kemungkinan pembacaan baru bahwa hukum dapat tetap tegas tanpa kehilangan sentuhan empati.
Di berbagai daerah, penerapan pendekatan restoratif mulai memperlihatkan bagaimana hukum dapat bergerak lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme mediasi penal, musyawarah komunitas, hingga penyelesaian berbasis adat menawarkan contoh bahwa keadilan tidak selalu hadir melalui putusan pengadilan. Dalam sejumlah kasus, proses dialog yang mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas justru menciptakan pemulihan yang lebih nyata dibandingkan putusan yang hanya bersandar pada logika penghukuman. Pendekatan ini membuka ruang bagi nilai kemanusiaan untuk bekerja, karena setiap pihak terlibat dalam proses pencarian solusi yang lebih peka terhadap pengalaman dan kerugian yang dirasakan.
Di tingkat kelembagaan, perkembangan menuju hukum yang berjiwa tampak dari mulai dibukanya ruang bagi interpretasi kontekstual, terutama pada perkara-perkara yang melibatkan masyarakat rentan. Beberapa hakim memberi pertimbangan atas kondisi sosial terdakwa, latar belakang ekonomi, hingga struktur sosial yang melingkupi perkara. Pertimbangan semacam itu memperlihatkan bahwa teks hukum dapat dibaca secara lebih hidup ketika ditempatkan dalam dialog dengan situasi empiris. Pendekatan ini memberi gambaran bahwa hukum dapat bergerak melampaui logika hitam-putih tanpa kehilangan struktur normatifnya.
Upaya membangun hukum yang berjiwa juga bertumpu pada kesadaran bahwa hukum beroperasi dalam masyarakat yang plural dan penuh lapisan pengalaman. Pluralitas tersebut menuntut kemampuan untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini kurang mendapat ruang dalam proses hukum, mulai dari perempuan, masyarakat adat, buruh, hingga kelompok marjinal lainnya. Ketika pengalaman mereka memperoleh tempat dalam argumentasi hukum, ruang perdebatan tidak lagi hanya dikuasai oleh bahasa teknis dan prosedural, tetapi juga oleh pengalaman hidup yang memperkaya pemahaman tentang keadilan. Dalam situasi seperti ini, hukum tampil sebagai wadah yang lebih inklusif.
Pembacaan baru terhadap hukum yang berjiwa juga menempatkan nilai keadilan sebagai orientasi yang hidup dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan bukan dipahami sebagai hasil akhir semata, tetapi sebagai proses yang melibatkan empati, kepekaan sosial, dan integritas moral. Dengan cara ini, hukum tidak dipandang sebagai perangkat yang bekerja secara otomatis, tetapi sebagai sistem yang memerlukan kesadaran etis dari para aktornya. Ketika aparat penegak hukum bergerak dengan orientasi demikian, hukum hadir bukan sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai ruang yang menampung keragaman pengalaman manusia.
Gagasan ini tidak mengingkari pentingnya kepastian hukum. Kepastian tetap menjadi fondasi bagi tertib sosial, tetapi fondasi tersebut memerlukan keterhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak berubah menjadi benteng yang membatasi pencapaian keadilan yang lebih luas. Keterhubungan antara kepastian dan keadilan memberi bentuk pada hukum yang tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga hangat dalam penerapannya. Pada titik inilah, hukum menemukan jiwanya ketika ia hadir sebagai jembatan antara aturan dan manusia, antara nalar dan empati, antara teks dan realitas.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemahaman baru tentang hukum yang berjiwa membuka ruang bagi pembaruan pemikiran hukum Indonesia. Pembaruan tersebut tidak sekadar menyasar perubahan regulasi, tetapi menyentuh cara berpikir, cara menafsirkan, dan cara merasakan hukum. Dengan demikian, hukum tidak bergerak sebagai mesin yang kaku, tetapi sebagai institusi yang berkembang bersama masyarakat. Pemahaman ini membawa harapan bahwa praktik hukum Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang tidak hanya tertib, tetapi juga adil dan bermakna bagi kehidupan publik.
Penutup
Membaca dinamika penegakan hukum Indonesia melalui kritik atas formalisme menunjukkan bahwa persoalan keadilan jauh melampaui sekadar kepatuhan pada teks normatif. Hukum tidak dapat dibangun hanya dengan logika deduksi dan kepastian prosedural; ia menuntut kepekaan terhadap manusia yang hidup di balik perkara. Ketika praktik hukum bergerak terlalu kaku, ia bukan hanya gagal merespons realitas sosial, tetapi juga berisiko menciptakan ketimpangan yang kian melebar antara mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang hanya bersandar pada harapan agar hukum berpihak pada kebenaran.
Kritik terhadap formalisme membuka ruang refleksi bahwa kebutuhan utama dalam pembaruan hukum Indonesia bukan sekadar memperbaiki aturan, tetapi menghidupkan kembali cara berpikir para aktor hukum. Jiwa hukum tidak hadir dari pasal demi pasal, melainkan dari kesediaan untuk membaca konteks, mendengarkan pengalaman masyarakat, dan menempatkan kemanusiaan sebagai orientasi etis dalam setiap keputusan. Pada titik inilah, gagasan mengenai “hukum yang berjiwa” menemukan relevansinya: ia bukan agenda utopis, melainkan kebutuhan praktis agar hukum dapat bekerja untuk semua, bukan hanya bagi mereka yang mampu menavigasi struktur formalnya.
Tantangan terbesar ke depan bukan lagi menyoal apakah hukum harus berubah, tetapi bagaimana perubahan itu dirancang agar tidak berhenti pada tataran kosmetik. Reformasi regulasi harus berjalan seiring dengan reformasi mentalitas: memperluas ruang interpretasi kontekstual, memperkuat sensitivitas sosial aparat penegak hukum, dan memastikan bahwa suara kelompok rentan tidak lagi terpinggirkan. Dengan demikian, hukum dapat tampil bukan sebagai institusi yang dingin dan jauh, tetapi sebagai sistem yang hadir, mendengar, dan menyembuhkan.
Pada akhirnya, keadilan substantif hanya dapat terwujud ketika hukum membuka diri terhadap kenyataan bahwa manusia berdiri di pusat setiap proses yuridis. Ketika hukum bergerak dengan nalar yang peka dan hati yang terarah pada kemaslahatan publik, ia menemukan kembali jiwanya. Dan ketika jiwa itu bekerja, hukum tidak lagi sekadar menjadi bangunan kokoh tanpa penghuni, tetapi menjadi rumah bersama—tempat di mana masyarakat dapat berharap, dipercaya, dan dilindungi. Pemulihan jiwa hukum inilah yang menjadi langkah krusial menuju masa depan penegakan hukum Indonesia yang lebih manusiawi, tangguh, dan adil bagi seluruh warganya.
Baca Juga: Eksistensi Restorative Justice Dalam Hukum Positif Indonesia