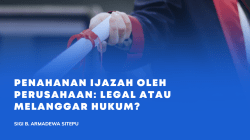Kita sedang berada di sebuah persimpangan, di mana dunia yang dulu kita kenal bergerak dengan ritme yang terukur, kini seolah dipaksa berlari mengikuti kecepatan teknologi. Revolusi digital telah merombak hampir seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bertransaksi. Namun, ada satu pilar besar peradaban yang secara naluriah cenderung konservatif dan bergerak lambat: hukum. Secara historis, hukum memang dirancang untuk menjadi jangkar yang menjamin kepastian dan stabilitas, ia cenderung lebih mengandalkan preseden daripada inovasi yang serba instan. Namun hari ini, jangkar itu sedang diuji oleh gelombang pasang teknologi yang tak kenal kompromi.
Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah hukum akan berubah, melainkan bagaimana kita mengarahkan perubahan itu agar tidak kehilangan esensi keadilannya. Di satu sisi, kita melihat janji yang begitu menggoda tentang demokratisasi akses terhadap keadilan. Bayangkan proses hukum yang dulu berbelit dan mahal, kini bisa dipangkas oleh efisiensi teknologi. Di Indonesia, kita sudah mulai merasakan euforia ini melalui lahirnya berbagai platform teknologi hukum yang membuat konsultasi menjadi lebih terjangkau dan penyelesaian sengketa kecil menjadi lebih cepat. Institusi peradilan pun mulai berbenah dengan sistem elektronik yang bertujuan memangkas birokrasi dan menutup celah korupsi. Ini adalah wajah baru hukum yang kita impikan: sebuah sistem yang terintegrasi mulus dalam kehidupan digital, memberikan perlindungan yang responsif dan nyata bagi setiap warga negara.
Baca Juga: Resensi Novel: Mengungkap Luka dan Keadilan dalam Bisikan Daun Jatuh
Namun, setiap lompatan besar selalu membawa bayang-bayang risiko yang tak kalah besar. Di balik optimisme efisiensi itu, tersembunyi ancaman yang bisa mereproduksi ketidakadilan dalam bentuk yang jauh lebih canggih dan sulit dideteksi. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang sering disebut sebagai bias algoritma. Kita harus sadar bahwa sistem kecerdasan buatan belajar dari data masa lalu. Jika data tersebut mengandung jejak diskriminasi atau ketidaksetaraan, maka sistem digital itu akan “belajar” untuk menjadi bias. Ia akan mengotomatisasi ketidakadilan dan memberinya stempel objektivitas palsu yang seolah-olah tidak bisa diganggu gugat karena dianggap sebagai hasil perhitungan matematis. Keadilan, bagaimanapun juga, tidak boleh menjadi sekadar produk sampingan dari sistem digital yang cacat sejak dalam pikiran.
Selain itu, kita juga menghadapi tantangan nyata berupa kesenjangan digital. Ketika layanan hukum beralih menjadi serba digital, ada risiko besar bahwa mereka yang berada di pelosok, para lansia, atau kelompok rentan lainnya akan semakin terpinggirkan. Digitalisasi yang tidak inklusif justru akan membangun tembok baru di atas jurang kesenjangan yang sudah ada. Kita tidak boleh membiarkan jembatan keadilan yang baru ini hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki akses dan literasi teknologi tinggi. Lebih jauh lagi, ada risiko dehumanisasi dalam proses hukum kita. Keadilan sejati membutuhkan lebih dari sekadar sistem digital; ia membutuhkan kebijaksanaan, empati, dan pemahaman mendalam tentang konteks kemanusiaan yang seringkali tidak bisa diterjemahkan ke dalam angka-angka. Hukum yang terlalu efisien berisiko kehilangan jiwanya, mereduksi manusia menjadi sekadar titik data dalam sebuah transaksi teknokratis.
Lantas, bagaimana kita menavigasi masa depan ini? Jalan keluarnya bukanlah dengan menutup diri dari teknologi, melainkan dengan mengendalikannya secara bijaksana melalui tata kelola yang adaptif dan tetap berpusat pada manusia. Kita membutuhkan kerangka aturan yang tidak hanya memfasilitasi inovasi, tetapi juga menetapkan batas-batas etis. Prinsip transparansi harus menjadi harga mati; setiap keputusan yang dihasilkan oleh teknologi harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, bukan menjadi sebuah “kotak hitam” yang misterius. Manusia—baik itu hakim, advokat, maupun regulator—harus tetap memegang kendali akhir atas keputusan-keputusan krusial yang menyangkut nasib sesamanya. Teknologi harus tetap menjadi abdi yang melayani, bukan tuan yang mendikte nurani kita.
Pada akhirnya, transformasi hukum di era digital adalah sebuah keniscayaan. Teknologi adalah pedang bermata dua yang kekuatannya bergantung pada siapa yang menggenggamnya. Arah yang akan kita tempuh sepenuhnya ditentukan oleh pilihan kolektif kita hari ini. Apakah kita akan membiarkan sistem digital mengambil alih rasa keadilan kita, ataukah kita akan menjadikannya alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata? Paradigma baru yang kita butuhkan adalah yang mengembalikan fokus pada manusia, memastikan bahwa di tengah gemuruh inovasi digital, hukum tetap memiliki hati dan keberpihakan pada mereka yang lemah. Itulah tanggung jawab moral kita untuk memastikan bahwa masa depan hukum kita tetap adil, manusiawi, dan berkelanjutan.