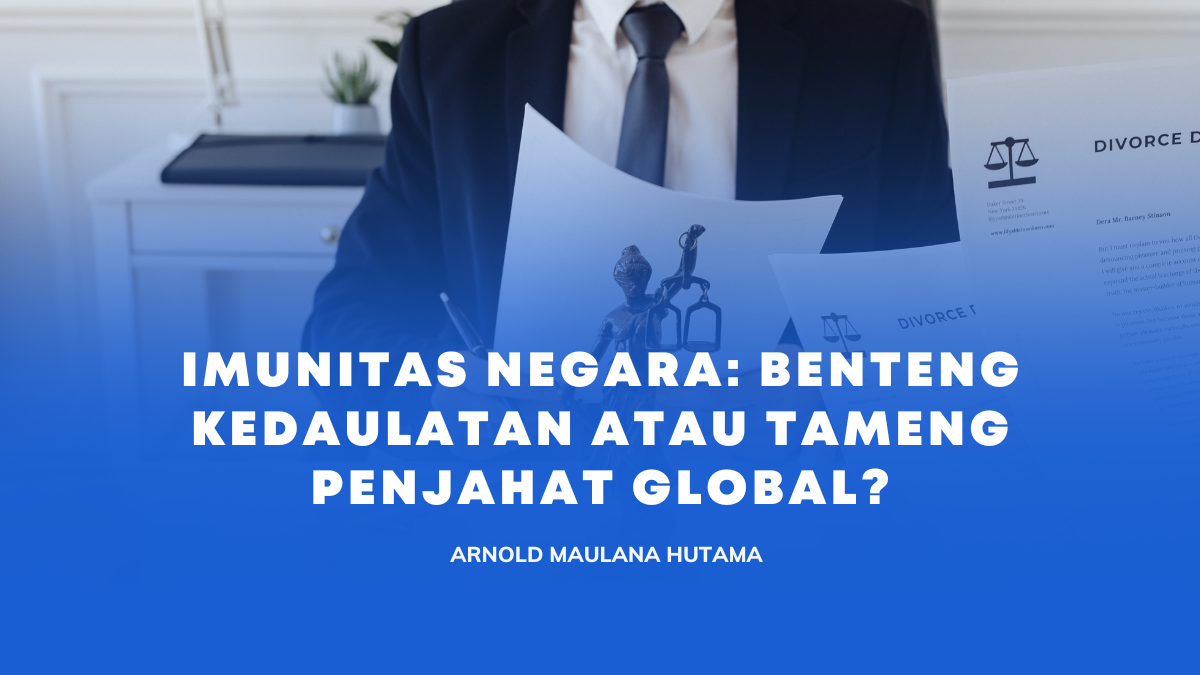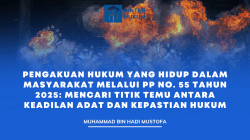Imunitas negara bagaikan perisai tak tertembus dalam dunia hukum internasional, yang mencegah suatu negara digugat atau diadili di pengadilan negara lain kecuali negara tersebut memberikan persetujuan terlebih dahulu. Prinsip ini lahir dari gagasan dasar kedaulatan, di mana setiap negara dianggap setara dan bebas dari campur tangan negara asing, sehingga menjaga perdamaian antar negara agar tidak saling serang lewat jalur hukum. Bayangkan saja tanpa imunitas ini, negara bisa dengan mudah menyeret negara lain ke pengadilan domestiknya hanya karena sengketa dagang atau klaim wilayah, yang berpotensi memicu konflik besar. Awalnya, imunitas ini bersifat mutlak di segala tindakan negara, baik urusan pemerintahan maupun bisnis, atau bisa di sebut juga kebal hukum. Namun, seiring arus globalisasi, konsep ini berevolusi menjadi imunitas terbatas, di mana hanya tindakan resmi pemerintah (seperti membuat undang-undang atau perang) yang dilindungi, sementara urusan komersial seperti jual beli minyak atau pinjaman bank harus tunduk pada hukum sipil biasa. Perubahan ini mencerminkan kenyataan bahwa negara modern tak lagi sekadar penguasa, tapi juga pemain pasar yang harus bertanggung jawab atas kesepakatan bisnisnya.
Tapi, di balik perlindungan, muncul isu kontemporer yang membuat imunitas negara jadi sorotan tajam: bagaimana kalau perisai ini justru melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan? Bayangkan kasus di mana pejabat tinggi negara melakukan penyiksaan massal atau genosida, lalu bersembunyi di balik imunitas saat korban ingin keadilan di pengadilan asing. Inilah dilema utama saat ini, terutama pasca Perang Dingin di mana hak asasi manusia (HAM) naik jadi prioritas global. Norma jus cogens yang berarti aturan hukum internasional yang tak boleh ditawar, seperti larangan genosida, perbudakan, atau penyiksaan. Kini dianggap bisa menembus imunitas negara. Artinya, kalau suatu tindakan melanggar aturan dasar ini, negara tak bisa lagi bilang “jangan ganggu urusan dalam negeri kami”. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Jerman vs Italia tahun 2012 menegaskan bahwa tindakan militer Perang Dunia II tak bisa digugat di pengadilan Italia karena imunitas negara, tapi putusan itu justru memicu perdebatan sengit soal batas kedaulatan versus keadilan. Di era 2025, dengan konflik seperti perang Ukraina atau ketegangan Timur Tengah, tuntutan ini makin kencang: apakah Rusia atau Israel bisa kebal tuntutan atas dugaan kejahatan perang hanya karena status negaranya??
Baca Juga: Imunitas Negara vs Hak Asasi Manusia: Siapa yang Menang dalam Kasus – Kasus Kontemporer?
Lebih dalam lagi, isu kontemporer ini terlihat jelas dalam praktik pengadilan hybrid dan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Pengadilan hybrid, seperti Special Court for Sierra Leone yang mengadili mantan Presiden Liberia Charles Taylor, membuktikan bahwa imunitas kepala negara bisa ditembus jika pengadilan dianggap “internasional” meski punya elemen nasional. Taylor divonis 50 tahun penjara atas kejahatan perang, meski awalnya mengklaim imunitas sebagai kepala negara. Tetapi, bukti bahwa hukum internasional mulai bergeser dari perlindungan mutlak ke akuntabilitas pribadi pejabat. ICC sendiri berdiri sejak 2002, telah menargetkan pemimpin seperti Omar al-Bashir dari Sudan atas genosida Darfur, meski penangkapannya terhambat karena negara-negara anggota PBB enggan menyerahkannya demi menjaga hubungan diplomatik. Di tahun 2025, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan untuk pejabat Rusia terkait invasi Ukraina, tapi eksekusinya mandek karena doktrin imunitas masih kuat di kalangan negara besar seperti AS, Rusia, dan China yang bukan penandatangan Statuta Roma. Ini menunjukkan paradoks bahwa lembaga global dibuat untuk keadilan, tapi terhambat oleh negara-negara berkuasa yang pakai imunitas sebagai senjata politik.
Tak berhenti di situ, globalisasi ekonomi menambah lapisan kompleksitas. Saat negara terlibat bisnis lintas batas seperti Saudi Arabia yang digugat di pengadilan AS atas serangan 11 September 2001. Imunitas terbatas sering dipakai untuk membedakan acta iure imperii (tindakan berdaulat) dan iure gestionis (tindakan komersial). Pengadilan AS akhirnya batalkan tuntutan Saudi karena dianggap tindakan berdaulat, tapi kasus serupa seperti Argentina gagal bayar utang membuatnya kalah di pengadilan hedge fund AS pada 2016, dan membayar miliaran dolar. Isu ini relevan di tahun 2025 dengan krisis utang negara berkembang pasca-pandemi COVID-19 dan perang dagang AS-China, di mana investor swasta menuntut negara-negara seperti Zambia atau Sri Lanka lewat pengadilan asing. Di sini, imunitas bukan lagi soal perang atau HAM, namun dalam ekonomi, apakah negara miskin boleh pakai imunitas untuk hindari bayar utang, atau harus tunduk pasar global demi tarik investasi? Reformasi seperti Konvensi PBB tentang Imunitas Negara di tahun 2004 yang mencoba atur ini, tapi diratifikasi kurang dari 30 negara saja, menunjukkan resistensi kuat.
Baca Juga: Amnesti dan Abolisi dalam Perspektif Sistem Presidensial
Lalu, bagaimana dengan Responsibility to Protect (R2P), doktrin PBB sejak 2005 yang izinkan intervensi jika negara gagal lindungi warganya dari genosida? R2P menguji imunitas negara secara frontal, seperti intervensi NATO di Libya 2011 yang jatuhkan Gaddafi atas pembantaian warga. Kritikus bilang ini penyalahgunaan, yakni intervensi jadi alat kuasai sumber daya, sementara pendukungnya melihat sebagai evolusi hukum di mana imunitas tak lagi melindungi tiran. Di tahun 2025, R2P diuji lagi di Myanmar atas genosida Rohingya atau Sudan atas konflik Darfur baru, tapi veto di Dewan Keamanan PBB oleh China-Rusia sering blokir aksi. Ini ungkap kelemahan struktural tentang imunitas negara kuat karena geopolitik, bukan menjadi hukum semata. Negara kecil seperti Islandia atau Selandia Baru dukung batasi imunitas untuk HAM, sementara raksasa seperti India atau Brasil ragu karena takut balik menggigit diri sendiri.
Pandemi COVID-19 juga bawa isu baru mengenai apakah negara bisa imunitas dari tuntutan atas kelalaian vaksin atau karantina? China digugat di Australia atas asal-usul virus, tapi klaim ditolak karena imunitas. Sementara itu, perusahaan farmasi negara seperti Sinovac lindungi lewat status BUMN, meski ada laporan efek samping. Ini soroti hybrid immunity campur imunitas negara dan korporasi. Di era AI dan cyberwar, isu makin rumit, serangan siber Rusia ke Ukraina 2022 apakah dilindungi imunitas sebagai “tindakan berdaulat”, atau bisa dituntut sebagai kejahatan hybrid? Pengadilan siber internasional belum matang, tapi kasus seperti itu paksa hukum internasional adaptasi cepat.
Upaya reformasi sedang bergulir. Uni Eropa via Foreign Sovereign Immunities Act batasi imunitas untuk korban terorisme, sementara Afrika Selatan dorong Afrika Union revisi imunitas kepala negara. Doktrin jus cogens diperkuat ICJ dalam kasus Gambia vs Myanmar 2019 soal Rohingya, di mana imunitas tak halangi investigasi HAM. Namun tantangan enforcement tetap lemah tanpa polisi global. Masa depan? Mungkin treaty baru yang tegas batasi imunitas untuk kejahatan berat, seperti proposed International Anti Corruption Court. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, posisi strategis ini mendukung reformasi HAM tapi menjaga imunitas untuk sengketa Laut China Selatan, di mana China klaim imunitas atas aktivitas militer.
Secara keseluruhan, imunitas negara di tahun 2025 bukan lagi benteng yang tak tergoyahkan, melainkan arena tarik-menarik antara kedaulatan dan keadilan. Prinsip ini lindungi negara dari kekacauan, tapi kalau disalahgunakan, jadi tameng diktator dan koruptor. Evolusi ke imunitas terbatas plus jus cogens tunjukkan hukum internasional hidup, adaptif. Tapi tanpa political will dari P5 PBB, reformasi mandek. Bagi kita warga Indonesia, di dunia multipolar hal krusial yang harus difahami adalah kedaulatan kuat tak berarti kebal hukum, tapi tanggung jawab global. Saatnya hukum internasional tak lagi “negara di atas segalanya”, tapi “kemanusiaan di atas kedaulatan” saat dibutuhkan. Dengan reformasi bijak, imunitas bisa jadi jembatan, bukan tembok, menuju dunia lebih adil.
Baca Juga: Hukum Tanpa Jiwa: Kritik atas Formalisme dalam Praktik Hukum Indonesia