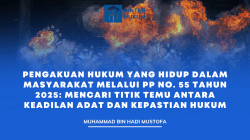Pada awal bulan Agustus lalu, publik dikejutkan oleh sebuah kebijakan yang menuai perhatian luas. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 mengenai pemberian amnesti serta Keppres Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pemberian abolisi. Berdasarkan ketentuan dalam kedua Keppres tersebut, Presiden memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana maupun narapidana, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Selain itu, presiden juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang lebih dikenal dengan sapaan Tom Lembong. Artinya dengan memberikan amnesti, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dihapuskan dan dengan memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap Tom Lembong ditiadakan
Keputusan tersebut mendapatkan respon yang beragam, sebagian kalangan menganggap pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.178 terpidana oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang berpotensi melemahkan konsistensi penegakan hukum di Indonesia, kendati memiliki dasar konstitusional.
Perlu kiranya disampaikan bahwa amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden dengan memeperhatikan petimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi negara Indonesia pada pasal 14 ayat (2).
Namun, menurut hemat penulis ada kejanggalan-Deharmonisasi antara konstitusi dan Undang-Undang. Jika kita tilik lebih dalam, UU amnesti dan abolisi di tetapkan dan diberlakukan pada desember 1954 yang mana, UU tersebut diperuntukan untuk napi rezim pra kemerdekaan, dan untuk melaksanakan UUDS 1950 yang artinya, UU ini sudah tidak relevan.
Baca Juga: Hapusnya Hak Untuk Menuntut dan Menjalani Hukuman
Apalagi UU tersebut tidak mengatur tindak pidana apa saja yang dapat diberikan amnesti dan abolisi. Hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat luas, Jika tidak diatur dengan jelas tindak pidana apa saja maka ini bisa jadi alat politik untuk menguntungkan kawan politik yang menjadi terpidana.
Maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan yang ideal terkait abolisi dan amnesti berdasarkan sistem pemerintahan presidensial?.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pengaturan mengenai amnesti dan abolisi seharusnya menekankan pada keseimbangan antara kewenangan prerogatif Presiden dengan prinsip check and balances. Pada dasarnya, pemberian amnesti maupun abolisi adalah instrumen politik-hukum yang melekat pada kekuasaan eksekutif, namun penerapannya tidak boleh bersifat absolut, melainkan tetap terkendali melalui mekanisme hukum maupun pengawasan lembaga yudikatif.
Jika dibandingkan, Amerika Serikat memberikan Presiden kewenangan luas dalam bentuk power to grant reprieves and pardons sebagaimana diatur dalam Article II Section 2 U.S. Constitution. Konstitusi tidak secara eksplisit membatasi jenis tindak pidana yang dapat diberikan pengampunan, sehingga kewenangan ini bersifat general, kecuali untuk perkara impeachment. Mekanisme pengampunan di Amerika lebih menekankan pada pertimbangan politik dan moral Presiden, dengan praktik administratif yang biasanya melibatkan Office of the Pardon Attorney di bawah Departemen Kehakiman.
Sementara itu, Filipina melalui Pasal VII Section 19 Konstitusi 1987, juga memberikan Presiden kewenangan luas untuk memberikan pardons, commutations, reprieves, and remission of fines and forfeitures, termasuk amnesti. Sama seperti Amerika, konstitusi Filipina tidak menetapkan batasan khusus terkait jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti atau abolisi. Satu-satunya pembatasan adalah perlunya persetujuan mayoritas Kongres untuk pemberian amnesti.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Presidensiil
Hal ini berlaku juga di Indonesia, di mana kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi tidak diatur secara jelas dalam konstitusi dan UU, Bisa kita lihat secara historis bukan hanya diperuntukkan bagi tindak pidana politik tetapi tindak pidana khusus. Hal tersebut bisa kita lihat di jaman presiden Jokowi dan presiden Prabowo.
Dari perbandingan tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengaturan ideal bagi Indonesia ke depan bukan sekadar meniru model Amerika atau Filipina yang memberi keleluasaan tanpa batasan, melainkan justru melengkapi dengan aturan yang tegas mengenai ruang lingkup tindak pidana. Idealnya, amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan untuk tindak pidana politik non-kekerasan atau perkara tertentu yang memiliki nilai rekonsiliasi nasional, sementara kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, narkotika skala besar, perdagangan orang, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi harus secara normatif dikecualikan.
Dengan demikian, Indonesia akan memiliki model pengaturan yang lebih proporsional: Presiden tetap memegang diskresi konstitusional, DPR berperan sebagai pengimbang politik, dan publik mendapat jaminan bahwa amnesti maupun abolisi tidak akan menjadi pintu penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Peran DPR dan Presiden dalam Pengesahan UU IKN: Analisis Kewenangan Berdasarkan Hukum Tata Negara