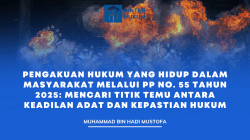Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat menandai salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah hukum internasional modern. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, seorang kepala negara yang masih menjabat ditangkap dan dibawa ke pengadilan negara lain melalui operasi lintas batas. Peristiwa ini bukan hanya soal kriminalitas atau politik domestik Venezuela, melainkan ujian serius terhadap prinsip dasar hukum internasional yang selama ini dijunjung: kedaulatan negara dan kesetaraan antarnegara.
Dalam hukum internasional, kepala negara bukanlah subyek hukum biasa .Ia si lindungi oleh prinsip imunitas kepala negara (Head of state immunity) yang telah ama menjadi fondasi hubungan antarnegara. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang kepala negara yang sedang menjabat tidak dapat ditangkap, ditahan, atau diadili oleh yuridiksi pidana negara lain. Imunitas ini bersifat imunitas personal (immunity ratione personae), melekat pada jabatannya, dan berlaku penuh selama masa jabatan.
Artinya, dalam kondisi normal, Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menangkap presiden Venezuela, meskipun AS menuduh yang bersangkutan melakukan kejahatan berat, termasuk pelanggaran HAM atau kejahatan transnasional. Penegakan hukum lintas negara tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan yang setara (sovereign equality of states), sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.
Penangkapan presiden Venezuela secara langsung menabrak prinsip ini dan membuka pertanyaan besar: apakah imunitas kepala negara masih relevan di era politik global yang semakin konfrontatif?
Pendukung tindakan Amerika Serikat berargumen bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, terutama jika dituduh melakukan kejahatan serius lintas negara seperti perdagangan narkotika dan kejahatan terorganisasi. Secara moral, argumen ini terdengar meyakinkan. Namun, dalam hukum internasional, moralitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa prosedur dan forum yang sah. Kejahatan internasional seharusnya diadili melalui mekanisme kolektif, seperti pengadilan internasional atau kerja sama ekstradisi berbasis persetujuan negara, bukan melalui tindakan unilateral yang mengabaikan kedaulatan.
Masalah menjadi semakin kompleks ketika melihat posisi Amerika Serikat dalam sistem hukum internasional. AS bukan negara pihak Statuta Roma dan tidak tunduk pada yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Ironisnya, negara yang menolak yurisdiksi internasional justru mengklaim kewenangan untuk menegakkan hukumnya sendiri terhadap kepala negara lain. Praktik ini menimbulkan kesan standar ganda dan memperkuat kritik bahwa hukum internasional sering kali digunakan secara selektif oleh negara kuat.
Sejak dua dekade terakhir, muncul dorongan kuat untuk menembus imunitas kepala negara, khususnya dalam kasus kejahatan internasional serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Di sinilah peran Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menjadi relevan.
Jika seorang presiden dituduh melakukan kejahatan internasional, penegakan hukumnya secara sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme internasional, bukan sepihak oleh satu negara. ICC dapat mengeluarkan surat penangkapan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kerja sama negara-negara anggota. Bahkan dalam konteks ini pun, praktik internasional masih sangat berhati-hati ketika menyentuh kepala negara yang sedang menjabat.
Kasus Presiden Sudan Omar al-Bashir sering dijadikan contoh. Meski ICC mengeluarkan surat penangkapan, banyak negara tetap enggan menangkapnya saat berkunjung, dengan alasan konflik antara kewajiban ICC dan prinsip imunitas kepala negara. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional belum sepenuhnya solid dalam mengatasi dilema antara keadilan global dan kedaulatan negara.
Bagaimana jika AS berdalih menggunakan yurisdiksi universal? Doktrin ini memang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa melihat kewarganegaraan atau lokasi kejahatan. Namun, penerapannya terhadap kepala negara aktif sangat diperdebatkan. Banyak ahli hukum internasional menegaskan bahwa yurisdiksi universal tidak otomatis menghapus imunitas kepala negara.
Jika penangkapan dilakukan tanpa mandat internasional, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk intervensi ilegal. Dampaknya tidak hanya hukum, tetapi juga geopolitik: preseden yang diciptakan oleh peristiwa ini sangat berbahaya. Jika penangkapan kepala negara oleh negara lain dianggap dapat dibenarkan, maka setiap negara kuat berpotensi mengkriminalisasi kebijakan politik negara lemah melalui hukum domestiknya. Hubungan internasional akan bergerak dari tatanan berbasis hukum menuju tatanan berbasis kekuasaan. Dalam kondisi demikian, hukum internasional kehilangan fungsinya sebagai pelindung negara-negara kecil dan berkembang.
Kasus ini juga menunjukkan keterbatasan konsep universal jurisdiction. Yurisdiksi universal seharusnya digunakan secara terbatas untuk kejahatan yang diakui secara universal, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dijalankan melalui mekanisme hukum yang transparan serta akuntabel. Ketika yurisdiksi universal diperluas secara sepihak untuk kepentingan nasional, ia berubah dari instrumen keadilan menjadi alat politik.
Reaksi internasional yang terbelah mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum global. Sebagian negara mengecam penangkapan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, sementara sebagian lain melihatnya sebagai langkah berani melawan impunitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum internasional belum memiliki mekanisme penegakan yang benar-benar konsisten dan bebas dari pengaruh politik kekuatan besar.
Bagi negara-negara berkembang, peristiwa ini menjadi peringatan keras. Ketergantungan pada perlindungan normatif hukum internasional tidak lagi cukup ketika kekuatan geopolitik mendominasi. Tanpa solidaritas internasional dan penguatan institusi multilateral, prinsip kedaulatan berisiko menjadi konsep simbolik semata.
Pada akhirnya, penangkapan Presiden Venezuela bukan hanya tentang satu individu atau satu negara. Ia adalah cermin rapuhnya tatanan hukum internasional di bawah tekanan kekuatan global. Jika hukum terus dikalahkan oleh kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah politik tanpa batas. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah komunitas internasional masih memiliki keberanian untuk menegakkan hukum secara setara, atau justru membiarkan hukum internasional larut menjadi bahasa legitimasi bagi yang paling kuat.
Baca Juga: Asas Hukum Internasional: Pengertian dan Implementasinya