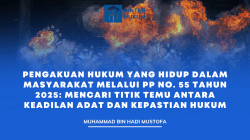Mari kita bersama-sama menunduk dan mengingat—karena kekejaman ini terlalu besar untuk dilupakan. Instansi yang kita harapkan sebagai penjaga keadilan, yang harusnya pelindung rakyat, malah berubah menjadi panggung kekuasaan yang memperlihatkan sisi paling kelamnya: dari Irjen Teddy Minahasa, sang Kapolda yang justru menjadi bandar sabu dengan 5 kg barang bukti diganti tawas, divonis seumur hidup—sebuah pengkhianatan terhadap amanah dan sistem akunabilitas internal seperti Propam dan Itwasum yang gagal mencegah korupsi moral; hingga Ferdy Sambo, yang seharusnya menjadi simbol penegakan etik internal malah menjadi pelaku utama pembunuhan dan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J, disertai para loyalisnya yang memanipulasi bukti, CCTV, dan saksi—dan lebih tragis lagi, beberapa di antaranya dianggap “selamat” lewat jabatan baru di tengah retakan integritas institusinya. Dan di puncak kesadisan ini, ada Affan Kurniawan, driver ojol berusia 21 tahun yang hanya menyeberang sambil mengantar pesanan demi sesuap nasi, tiba-tiba menjadi korban—dilindas oleh rantis (Brimob) di tengah demo buruh yang membawa amarah rakyat lebih besar daripada senjata mereka.
Dampaknya memantik protes nasional, tuntutan reformasi Polri, serta hashtag menyayat hati seperti #PolisiPembunuhRakyat—sementara tujuh anggota Brimob itu diperiksa live oleh Propam di Mabes Polri, mengenakan kaos hijau “Titipan Divpropam”, mata kosong menunduk, simbol formalitas etik yang menggema hampa (salah satunya: pengakuan sopir rantis yang panik dan mengaku tak melihat karena kaca gelap dan asap tebal. Inilah tragedi institusi yang gagal melindungi, dan malahan menjadi ancaman—sebuah panggilan keras: tanpa membenahi kultur sistemik, keamanan hanya menjadi alat bencana, dan keadilan semakin menjauh. Reformasi tak bisa berhenti di penindakan oknum—ia harus merambah ke jantung sistem yang memungkinkan kekuasaan tanpa kontrol. Reformasi mutlak untuk membalikkan stigma dan membangun kepercayaan rakyat kembali ke pangkuan hukum, bukan mesin kekuasaan yang keji.
Baca Juga: Kriminalisasi Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia
Nah, ini justru titik renungan paling pedih. Kalau yang duduk di kursi terdakwa itu bukan jenderal, bukan perwira, bukan anggota korps—tapi rakyat jelata, mahasiswa, atau ojol biasa—proses hukum pasti beda rasa. Mari kita uji pakai logika sederhana hukum acara pidana:
Teddy Minahasa (sabu 5 kg)
Kalau pelakunya bukan Kapolda? Coba bayangkan seorang kurir atau rakyat biasa kedapatan membawa sabu 5 kg. Jangan harap vonis seumur hidup jadi opsi; rata-rata mereka langsung dihantam hukuman mati dengan dalih pemberantasan narkoba tanpa ampun. Tapi Teddy? Vonisnya seumur hidup, plus selalu ada gosip peluang PK, kasasi, atau remisi di ujung jalan. Ada “ruang abu-abu” yang hanya bisa dipijak karena pangkat.
Ferdy Sambo (pembunuhan berencana)
Kalau pelakunya rakyat sipil biasa, skenario minimumnya hukuman mati tanpa drama. Tidak akan ada panggung obstruction of justice yang ditolerir; semua pelaku ikut masuk jeruji tanpa pangkat yang bisa jadi pelindung. Tapi Sambo? Hukuman mati dikurangi jadi seumur hidup, diselimuti framing media, dan sebagian loyalisnya malah sempat mendapat promosi. Kalau rakyat jelata? Jangan mimpi! Bahkan saksi kecil bisa “ikut hanyut” dalam jerat pidana.
Baca Juga: Hambatan dan Tantangan dalam Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi
Kasus Affan (korban rantis Brimob)
Kalau posisi terbalik—misalnya seorang warga sipil yang mengendarai truk lalu melindas anggota Brimob di lapangan—dijamin sudah diproses pasal pembunuhan berencana (340 KUHP) atau minimal penganiayaan yang menyebabkan kematian (351 ayat 3 KUHP), dengan tahanan penuh tanpa jeda, dan kemungkinan besar langsung dituntut maksimal. Tapi karena pelakunya aparat? Yang muncul justru sidang etik, pengakuan “panik” dan “tidak melihat,” seakan hukum bisa dilunakkan hanya dengan alasan prosedural.
Polanya Jelas
Pasal hukum ternyata elastis—bisa keras menghantam rakyat jelata, tapi lentur ketika menyentuh seragam berbintang. Padahal KUHP tidak pernah membedakan “siapa” pelaku, hanya “apa” perbuatannya. Yang kita lihat hari ini bukan sekadar hukum formal, tapi hukum feodal: keras ke bawah, lembut ke atas.