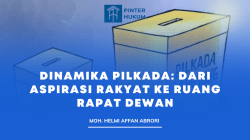Bayangkan, kamu sedang menyaksikan bahwa ada sebuah negara yang tega sama rakyatnya sendiri. Orang-orang disiksa, ribuan dibunuh, etnis tertentu diusir dari tanah kelahirannya. Semua orang tahu, berita bertebaran, foto korban viral, organisasi HAM teriak minta keadilan. Tapi begitu kasusnya masuk ke pengadilan internasional, negara itu cuma angkat bahu, negara itu berkata: “Kami punya imunitas, Anda tidak bisa mengadili kami.”
Nah, di titik ini kita langsung mikir: kalau negara bisa sembunyi di balik tameng imunitas, nasib korban gimana? Apakah HAM bisa benar-benar menang kalau negara sendiri yang jadi pelaku?
Dalam hukum internasional, negara memang punya “imunitas” perlindungan agar tidak mudah diseret ke pengadilan negara lain. Tujuannya baik, untuk menjaga hubungan antarnegara tetap stabil dan mencegah intervensi asing. Bayangin kalau tiap negara bisa saling seret ke pengadilan, dunia bisa chaos. Namun, masalah muncul ketika negara justru melakukan pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, komunitas internasional menjunjung prinsip perlindungan HAM yang bersifat universal.
Tapi di sisi lain, ada nilai yang nggak bisa ditawar, hak asasi manusia. Genosida, penyiksaan, pembersihan etnis itu kejahatan yang nggak boleh dilindungi siapa pun, bahkan oleh kedaulatan negara. Benturan pun terjadi: mana yang harus diutamakan kedaulatan negara atau hak manusia untuk hidup dan dibela? Pertanyaan ini jadi inti konflik di berbagai belahan dunia, dari Kosovo, Myanmar, hingga Suriah.
Baca Juga: 5 Bentuk Tindakan Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Israel Terhadap Warga Sipil
Imunitas Negara, HAM, dan Prinsip Non-Intervensi: Tiga Pilar yang Sering Berbenturan
Imunitas negara lahir dari prinsip kesetaraan antarnegara, satu negara tidak boleh seenaknya mengadili negara lain. Ditambah prinsip non-intervensi, urusan dalam negeri dianggap “wilayah suci” yang tidak boleh disentuh pihak luar. Logikanya sederhana, setiap negara punya pagar rumah sendiri, dan tetangga tidak boleh sembarangan masuk.
Tapi kalau negara justru jadi pelaku pelanggaran HAM, alasan “urusan internal” jadi absurd. HAM itu universal, dampaknya global. Pelanggarannya bukan lagi urusan internal, melainkan ancaman terhadap kemanusiaan. Dilema besar pun akhirnya muncul, apakah dunia harus diam demi menghormati kedaulatan, atau bergerak demi menyelamatkan manusia?
Apakah Imunitas Negara Perlu Pengecualian untuk Pelanggaran HAM Berat?
Banyak ahli menegaskan bahwa imunitas tidak boleh jadi perisai untuk menutupi kejahatan luar biasa seperti genosida atau kejahatan perang. Namun, beberapa negara tetap bertahan dengan alasan kedaulatan dan stabilitas politik. Organisasi internasional mencoba mencari jalan tengah: menghormati kedaulatan, tapi tetap membuka ruang intervensi jika pelanggaran HAM sudah mencapai level darurat kemanusiaan.
Di titik inilah muncul perdebatan panjang: apakah kedaulatan negara masih bisa dijadikan alasan ketika nyawa manusia dipertaruhkan? Banyak kalangan menilai bahwa konsep imunitas harus berevolusi, dari sekadar melindungi hubungan antarnegara menjadi mekanisme yang tetap memberi ruang bagi keadilan. Dunia internasional mulai menyadari bahwa jika imunitas dipertahankan secara kaku, maka korban pelanggaran HAM berat akan terus kehilangan akses terhadap keadilan. Sebaliknya, jika imunitas diberi pengecualian dalam kasus ekstrem, maka ada harapan bahwa hukum internasional benar-benar bisa menjadi pelindung bagi martabat manusia.
Upaya Negara dan Organisasi Internasional Mencari Keseimbangan
Berbagai mekanisme mulai dikembangkan untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM.
- Pengadilan HAM internasional seperti ICJ dan ICC hadir sebagai arena hukum global: ICJ menangani sengketa antarnegara, sementara ICC fokus menuntut individu pelaku kejahatan berat. Jadi, meski negara bersembunyi di balik imunitas, para pejabat atau aktor yang bertanggung jawab tetap bisa dijerat.
- Selain itu, ada sanksi diplomatik dan ekonomi. Negara pelanggar bisa dikucilkan dari pergaulan internasional, dibatasi akses perdagangan, atau kehilangan dukungan politik. Tekanan ini membuat mereka sadar bahwa pelanggaran HAM tidak hanya soal moral, tapi juga punya konsekuensi nyata bagi stabilitas ekonomi dan reputasi global.
- Kemudian muncul konsep “Responsibility to Protect” (R2P). Prinsip ini menegaskan: kalau negara gagal melindungi rakyatnya, komunitas internasional punya tanggung jawab moral dan legal untuk turun tangan. R2P jadi dasar intervensi kemanusiaan, meski sering menimbulkan perdebatan soal batas legalitasnya.
- Terakhir, ada pembatasan imunitas dalam kasus tertentu. Beberapa negara mulai membuka celah hukum agar imunitas tidak berlaku untuk kejahatan luar biasa seperti penyiksaan atau genosida. Ini menunjukkan tren global yang makin jelas: imunitas negara tidak boleh absolut. Dunia bergerak ke arah baru, di mana kedaulatan tetap dihormati, tapi tidak bisa lagi dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan kemanusiaan.
Studi Kasus: Genosida Kosovo
Kosovo jadi titik balik penting di akhir 1990-an. Rezim Serbia dituduh melakukan pembersihan etnis terhadap warga Albania-Kosovo: pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran besar-besaran. Serbia bersembunyi di balik prinsip non-intervensi dan imunitas negara, seolah tragedi itu hanya “urusan internal.”
Tapi dunia tidak tinggal diam. NATO turun tangan lewat intervensi militer tanpa persetujuan Serbia. Kontroversial? Ya. Tapi langkah itu menunjukkan satu hal: ketika negara gagal melindungi rakyatnya, komunitas internasional merasa berhak melangkahi imunitas demi kemanusiaan. Kosovo pun jadi pelajaran bahwa kedaulatan bukan alasan untuk menutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan.
Dilema Kedaulatan vs Kemanusiaan
Apa yang sebenarnya terjadi di titik ini? Konfliknya sederhana tapi tajam, negara ingin mempertahankan kedaulatannya, sementara dunia ingin mencegah kejahatan yang merusak martabat manusia.
Dilema besarnya jelas. Kalau imunitas negara dihapus total, hubungan antarnegara bisa goyah bayangkan domino yang jatuh satu per satu, memicu ketidakstabilan global. Tapi kalau imunitas dipertahankan secara absolut, pelanggaran HAM bisa dibiarkan tanpa ada mekanisme pertanggungjawaban. Korban hanya bisa menunggu keadilan yang tak pernah datang.
Kosovo memberi pelajaran penting, dalam situasi ekstrem, dunia mulai condong ke perlindungan HAM. Meski langkah intervensi NATO saat itu menimbulkan perdebatan panjang soal legalitas, pesan moralnya kuat ketika nyawa manusia dipertaruhkan, kedaulatan tidak bisa jadi alasan untuk diam.
Kesimpulan: Mencari Titik Keseimbangan
Pertarungan antara imunitas negara dan HAM ternyata bukan soal siapa yang lebih kuat, melainkan soal bagaimana dunia menemukan titik keseimbangan. Kosovo menunjukkan bahwa dalam kasus ekstrem, perlindungan HAM bisa “memenangi” konflik ini, meskipun secara hukum masih penuh perdebatan. Intinya jelas: kedaulatan negara penting, tetapi martabat manusia jauh lebih penting.
Ke depan, muncul pertanyaan besar: apakah dunia memerlukan aturan internasional baru yang memperjelas batas imunitas negara? Atau justru kita butuh mekanisme global yang lebih cepat dan tegas untuk mencegah pelanggaran HAM berat? Pertanyaan ini bukan hanya untuk para pemimpin dunia, tetapi juga untuk kita sebagai warga global. Karena pada akhirnya, dilema ini menyangkut masa depan kemanusiaan, apakah kita memilih stabilitas semu, atau keberanian untuk menegakkan keadilan nyata.
Baca Juga: Amnesti dan Abolisi dalam Perspektif Sistem Presidensial
Referensi
Akande, Dapo. “International Law and Human Rights: The Conflict Between State Immunity and Accountability.” European Journal of International Law, 2010.
Huala Adolf. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
International Court of Justice – Germany v. Italy (Jurisdictional Immunities of the State), 2012.
Paulina Dewi. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2012.
Shaw, Malcolm N. International Law. Cambridge University Press, 2017.