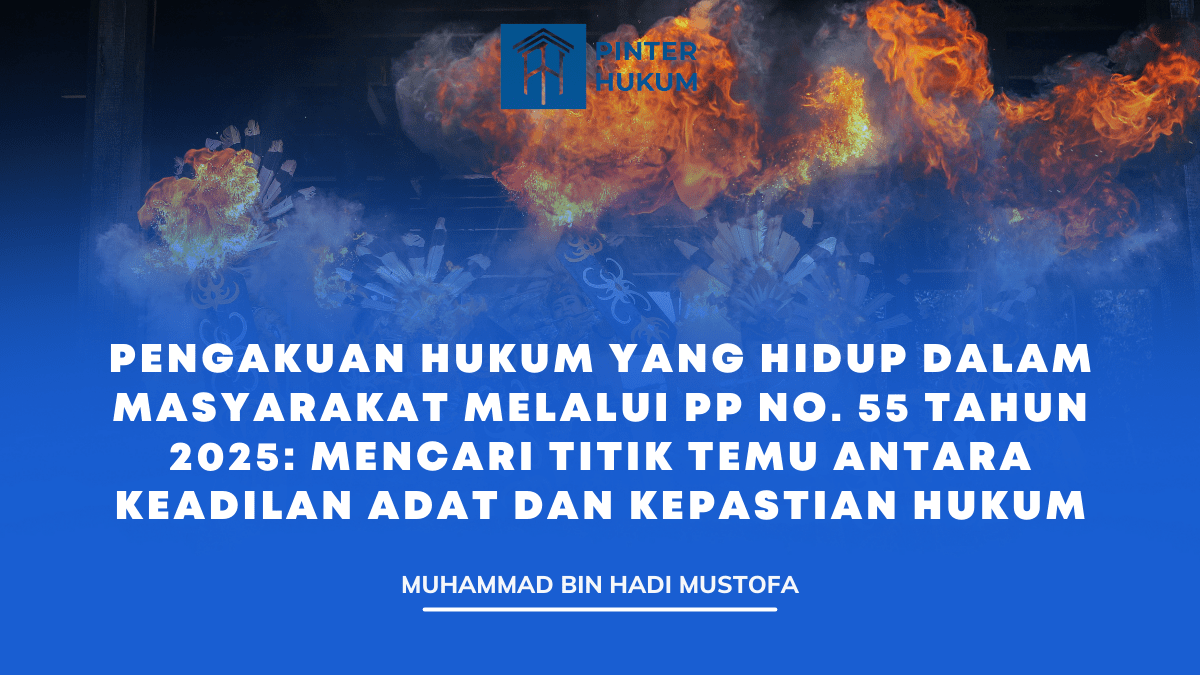Perdebatan tentang posisi living law dalam sistem hukum nasional Indonesia kembali menemukan relevansinya setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Jika sebelumnya hukum pidana Indonesia cenderung berkarakter positivistik dan berorientasi pada teks undang-undang, KUHP Baru membuka babak baru dengan mengakui asas legalitas materiil yang memberi ruang bagi keberlakuan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk mengoperasionalkan ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Regulasi ini dimaksudkan sebagai pedoman agar pengakuan terhadap hukum adat tidak berjalan asal-asalan.
Indonesia merupakan negara dengan corak pluralisme hukum yang kuat. Di samping hukum negara yang tertulis (state law), Indonesia juga mengakui adanya hukum adat, norma agama, dan kebiasaan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam banyak komunitas adat, norma-norma tersebut tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dianggap lebih efektif karena lahir dari nilai-nilai lokal yang sudah dipercaya sejak dahulu. Ironisnya, sistem hukum modern sering kali mengabaikan realitas ini dengan berpegang teguh pada paradigma positivisme hukum yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi pemidanaan, yaitu Asas Legalitas.
Baca Juga: Hukum sebagai Kaidah: Memahami Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya
Asas legalitas dalam tradisi hukum pidana klasik dipahami secara ketat sebagai nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, yang artinya “tidak ada pidana tanpa undang-undang yang terlebih dulu mengaturnya”. Prinsip ini lahir sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut di Eropa, di mana penguasa dapat menghukum tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana” yang menjelaskan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai pelindung warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Namun, pendekatan yang terlalu positivistik sering kali gagal menangkap rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama di negara dengan banyak kemajemukan seperti Indonesia.
Secara historis, pengakuan terhadap hukum adat dalam hukum pidana Indonesia bukanlah hal baru. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 pernah mengakui keberlakuan delik pidana adat, meskipun perbuatannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, pembentuk undang-undang menyadari keterbatasan hukum tertulis dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.
Namun, pengakuan tersebut belum pernah diatur secara sistematis hingga lahirnya KUHP Baru. Dalam Pasal 2 KUHP Baru secara eksplisit mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana, meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju legalitas material. Negara tidak lagi semata-mata bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga mengakui nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
PP No. 55 Tahun 2025 memainkan peran strategis. Sebagai aturan pelaksana Pasal 2 ayat (3) sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam KUHP Baru, PP ini bertujuan memberikan kepastian prosedural dalam penerapan living law. Dalam Pasal 1 ayat (1), hukum yang hidup dalam masyarakat didefinisikan sebagai hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Pasal 1 ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa Tindak Pidana Adat adalah tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
Definisi ini menunjukkan bahwa PP No. 55 Tahun 2025 tidak hanya mengakui eksistensi hukum adat, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan ini tidak bersifat tanpa batas. Peraturan tersebut menetapkan kriteria ketat agar suatu norma adat dapat diakui sebagai dasar pemidanaan. Pertama, norma tersebut harus benar-benar masih hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat. Artinya, bukan sekadar norma yang pernah ada di masa lalu, tetapi masih dipraktikkan secara nyata dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Pembatasan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap kearifan lokal dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Negara ingin menghindari legitimasi terhadap praktik adat yang diskriminatif, melanggar HAM, atau bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.
Baca Juga: Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau
Selain itu, PP No. 55 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengakuan living law tidak bersifat otomatis. Harus ada proses penilaian dan pembuktian mengenai keberlakuan norma adat dalam komunitas tertentu. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai filter agar norma adat yang diterapkan benar-benar representatif, masih relevan, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Dengan demikian, negara tetap mempertahankan kontrol konstitusional atas norma adat yang akan dijadikan dasar pemidanaan.
Meskipun prinsip lex certa dalam Asas Legalitas menuntut agar rumusan perbuatan pidana harus jelas, tegas, dan tidak interpretatif, sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang. Dalam konteks living law, tantangan ini semakin besar karena norma adat sering kali bersifat kontekstual, tidak tertulis, dan bergantung pada interpretasi kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi individu yang berasal dari luar kelompok adat tersebut.
Dalam perspektif teori hukum, pengakuan living law sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich, yang berpendapat bahwa hukum yang efektif bukanlah hukum yang tertulis dalam buku, melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Namun, dalam konteks negara modern, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan konsep ini ke dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan HAM. PP No. 55 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai upaya institusionalisasi living law. yakni usaha negara untuk mengakui, mengatur, dan mengendalikan keberlakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Ini adalah langkah progresif karena sebagai bentuk mengakui pluralisme hukum Indonesia. Namun, progresivitas ini harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurut saya, ada tiga prasyarat utama agar pengakuan living law melalui PP No. 55 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan adil. Pertama, perlu ada pedoman teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pembuktian keberlakuan hukum adat, termasuk standar pembuktian, peran ahli adat, dan dokumentasi norma adat. Kedua, perlu peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum adat, antropologi hukum, dan pluralisme hukum. Ketiga, perlu mekanisme pengawasan agar penerapan living law tidak menyimpang dari prinsip HAM dan prinsip non-diskriminasi.
PP No. 55 Tahun 2025 mencerminkan kompromi antara dua nilai fundamental, yakni kepastian hukum dan keadilan substantif. Negara berusaha mempertahankan asas legalitas, tetapi juga mengakui bahwa keadilan tidak selalu lahir dari teks undang-undang semata. Tantangan kita ke depan adalah memastikan bahwa pengakuan terhadap living law tidak menjadi pintu masuk bagi ketidakpastian dan ketidakadilan, akan tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih tepat dan bermakna bagi masyarakat.
Baca Juga: Tantangan Hukum Adat: Aksi Solidaritas Merauke Tolak Proyek Strategis Nasional