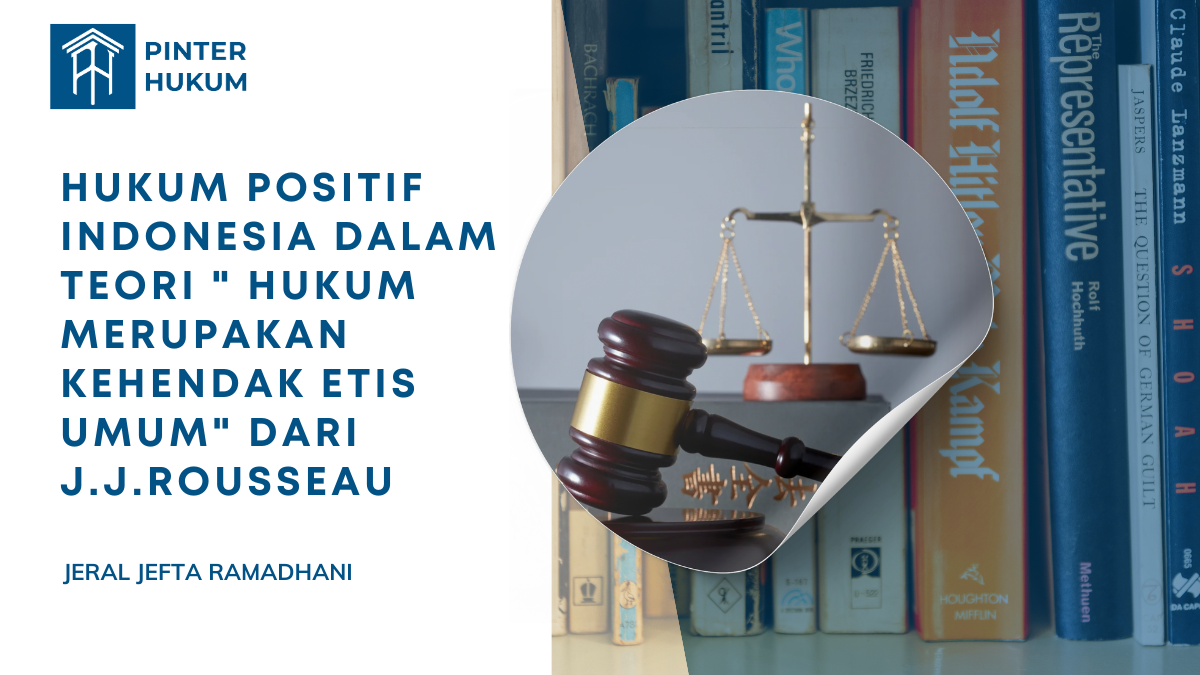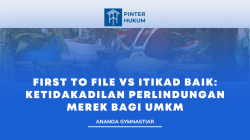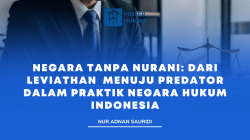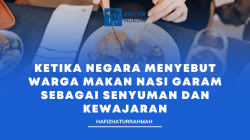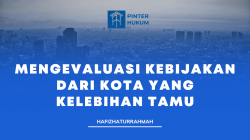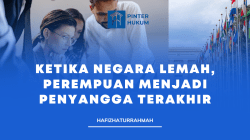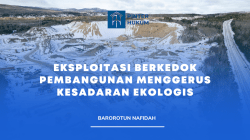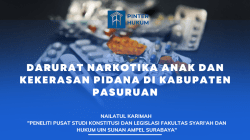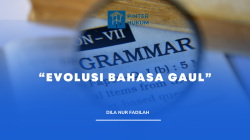Hukum positif di Indonesia merupakan produk dari proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yang seyogyanya mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat secara umum. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak dinamika yang menyebabkan hukum positif seringkali tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait hakikat hukum itu sendiri, khususnya dalam konteks etika dan keadilan sosial.
Jean Jasques Rousseau merupakan seorang penulis dan filsuf yang hidup pada zaman Aufklarung atau zaman pencerahan pada tahun 1712-1778. Belau mengembangkan bahwa Hukum merupakan kehendak etis umum berlandasan sebuah pertanyaan yang muncul dalam pikirannya sendiri bahwa “ Mengapa manusia yang semua merupakan entitas konkret yang merdeka, bebas, dan alamiah menjadi entitas yang terbelenggu oleh adanya sebuah peraturan?” maka dari itu terbitlah teori bahwa hukum merupakan kehendak etis umum. Bahwa menurut Rousseau mengatakan hukum itu milik pribadi dan bersifat obyektif, artinya hakekat dari hukum merupakan kemauan umum bukan merupakan kemauan golongan tertentu dan maksud dari bersifat obyektif adalah kondisi yang alamiah atau natural. Dan memiliki fungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus dengan kepentingan pribadi. “Kehendak Umum” Rousseau, yang merupakan terjemahan dari bahasa Prancis ” volonté générale “, juga dapat disebut sebagai “kehendak rakyat”. Singkatnya, ini adalah kehendak atau keinginan kolektif rakyat. Bagi Rousseau, kehendak umum bersifat umum, baik dari segi siapa yang menghendakinya maupun objeknya. Dengan demikian, di satu sisi, kehendak umum mengacu pada apa yang dikehendaki oleh rakyat secara keseluruhan. Di sisi lain, kehendak umum mengacu pada norma, hukum, prinsip, nilai, lembaga, dll. yang dikehendaki oleh suatu kelompok masyarakat sebagai objek.
Baca Juga: Tantangan Legal Tech dalam Transformasi Layanan Hukum Perdata: Peluang dan Resiko
Hukum positif Indonesia yang menganut teori dari hans kelsen yaitu teori hukum murni yang dimana memiliki ciri-ciri yaitu hukum yang dikodifikasikan dan memiliki Grundnorm yaitu pancasila seyogyanya bangsa ini sudah dalam koridor yang bagus jikalau dinamika hukum berpandangan pada prinsip-prinsip dari Pancasila. Saya juga mengambil dari teori Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum memiliki 3 komponen jika ingin hukumnya bagus yaitu:
- Legal Structure
Artinya bahwa hukum yang bagus juga berasal dari siapa yang menggerakkan dan menegakkannya, contohnya adalah pengadilan, polisi, dan lembaga penegak hukum yang lain.
- Legal Substance
Artinya bahwa isi dari muatan peraturan / norma yang dibuat haruslah berkuallitas dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
- Legal Culture
artinya bahwa sikap dan kebiasaan dari unsur masyarakat juga mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan dipatuhi.
Baca Juga: Peran Hakim dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon
Ketika teori dari Friedman tersebut katakanlah sudah terpenuhi maka dapat dipastikan sebuah sistem hukum di Indonesia pastilah terjamin dan bagus. Kembali pada teori dari Roesseau “ Hukum merupakan kehendak etis umum “ dapat saya pertegas bahwa hukum positif di Indonesia yang merupakan produk dari lembaga legislatif yang dimana disusun oleh DPR dan Presiden seyogyanya memang berpihak kepada masyarakat, agar tujuan dari latar belakang teori ini tercapai. Bahwa memang manusia haruslah merdeka, alamiah, dan bebas sesuai dengan peraturan yang di buat dan disepakati.
Namun pada kenyataannya, banyak dari produk yang di buat oleh lembaga legislatif sudah banyak yang tidak berpihak pada masyarakat. Mengakibatkan kemerdekaan dari masyarakat tidak tercapai. Saya beri contoh yaitu Undang-Undang Cipta kerja ( Omnibuslaw ) yang tidak berpihak pada buruh dan malah menguntungkan dari para pemilik modal, lalu juga ada peristiwa Mahkamah Konstitusi merealisasikan batasan usia Capres dan Cawapres yang pada masa itu ditujukan kepada salah satu paslon, dll. artinya memang pembentukan peraturan di Indonesia ini seringkali tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Perjanjian Kerja Sebagai Special Agreement Antara Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan
Sebagai kesimpulan, teori hukum sebagai kehendak etis umum dari Jean-Jacques Rousseau memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pemahaman hukum positif Indonesia. Hukum tidak semata-mata produk regulasi formal, melainkan harus mencerminkan kehendak kolektif masyarakat yang menjunjung keadilan dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum positif di Indonesia perlu senantiasa dikaji agar selaras dengan nilai-nilai etika dan kepentingan bersama, bukan hanya sebagai instrumen mekanis penataan sosial. Kritik dan analisis menggunakan perspektif Rousseau ini menjadi penting sebagai refleksi dan evaluasi agar hukum positif Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga tatanan kenegaraan yang adil dan bermartabat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperdalam kajian ini dengan mengintegrasikan aspek empiris dan kebijakan konkrit agar hukum benar-benar menjadi wahana kehendak etis umum di tengah masyarakat yang plural dan dinamis.