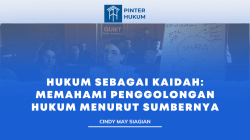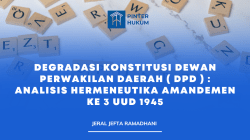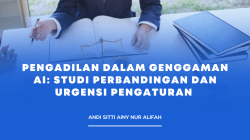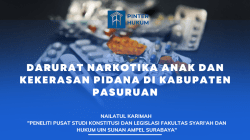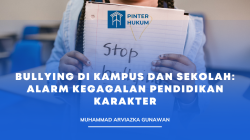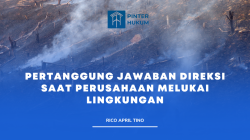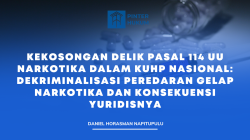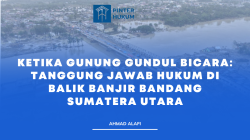Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (umum dikenal sebagai KUHAP), Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi kemudian mengalami perluasan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga saksi juga dapat mencakup “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Peran saksi dalam proses peradilan pidana memiliki posisi yang sangat penting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama, mendahului alat-alat bukti lainnya, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.
Dalam ketentuan KUHAP, kewajiban saksi diatur dengan cukup tegas untuk menjamin keabsahan dan kejujuran keterangan yang diberikan di persidangan. Sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, sebagai bentuk komitmen bahwa seluruh keterangan yang akan disampaikan merupakan kebenaran yang sebenarnya. Setelah memberikan keterangan, saksi juga memiliki kewajiban untuk tetap berada di ruang sidang hingga mendapatkan izin dari hakim ketua untuk meninggalkannya. Selain itu, selama proses persidangan berlangsung, saksi dilarang melakukan percakapan yang dapat memengaruhi jalannya pemeriksaan atau objektivitas kesaksiannya.
Baca Juga: Nepotisme Termasuk dalam Perkara Pidana atau Perdata?
Saksi memiliki sejumlah hak yang harus dijamin sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Seorang saksi berhak dipanggil secara resmi oleh penyidik melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar serta berhak mengetahui alasan pemanggilan tersebut. Apabila saksi tidak dapat hadir karena alasan yang patut dan dapat diterima, ia berhak meminta agar pemeriksaan dilakukan di tempat kediamannya. Selain itu, saksi dijamin haknya untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun. Saksi juga memiliki hak untuk menolak menandatangani berita acara pemeriksaan jika terdapat keberatan yang beralasan terhadap isi keterangannya. Dalam proses pemeriksaan, saksi tidak boleh diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. Lebih lanjut, apabila saksi tidak memahami bahasa Indonesia, ia berhak mendapatkan bantuan dari seorang juru bahasa. Begitu pula bagi saksi yang bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, berhak atas penerjemah yang dapat membantunya berkomunikasi dengan benar selama proses hukum berlangsung.
Saksi dalam perkara atau peradilan pidana sendiri ada beragam jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Saksi Memberatkan (a charge)
Saksi yang memberatkan, atau disebut juga a charge, merupakan saksi yang memberikan keterangan yang dapat memberatkan posisi terdakwa dalam persidangan. Umumnya, jenis saksi ini dihadirkan oleh pihak penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang keterangannya dapat memberatkan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, alat bukti yang pertama kali diperiksa adalah keterangan dari saksi a charge atau saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Ketentuan mengenai penggunaan saksi a charge diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:
- Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Meringankan (a de charge)
Saksi yang meringankan, atau disebut juga a de charge, merupakan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dengan tujuan untuk mendukung pembelaan terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Keberadaan saksi ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 65 KUHAP yang berbunyi, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Dasar hukum lain dari saksi a de charge juga terdapat pada pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”. Saksi a de charge memiliki peran penting dalam proses pembuktian di pengadilan, karena kehadirannya dapat menyeimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Kehadiran saksi a de charge bergantung pada keinginan tersangka untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangannya, baik pada tahap penyidikan maupun proses selanjutnya. Apabila tersangka tidak menghendaki kehadiran saksi tersebut selama penyidikan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menghadirkan saksi a de charge.
3. Saksi ahli
Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, pendidikan, atau pengalaman khusus dalam bidang tertentu yang diminta untuk memberikan keahliannya dalam proses hukum guna membantu pengadilan memahami isu-isu teknis atau ilmiah yang kompleks. Saksi ahli juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan serta keahlian khusus terkait hal yang disengketakan, yang memberikan penjelasan dan informasi tambahan kepada hakim untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan perkara.
4. Saksi korban
Saksi korban merupakan pihak yang menjadi korban dalam suatu perkara dan disebut sebagai saksi karena perannya yang secara langsung mendengar, melihat, serta mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
5. Saksi de auditu
Saksi de auditu merupakan saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain, bukan dari pengalaman atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang dimaksud. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengakui kesaksian testimonium de auditu, yaitu keterangan yang diberikan saksi berdasarkan apa yang didengarnya dari orang lain, sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian saksi sehingga kesaksian testimonium de auditu kini juga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Namun demikian, tidak semua perkara pidana dapat menerapkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam tahap pembuktiannya. Kesaksian testimonium de auditu hanya dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh fakta lain yang relevan dan saling berkaitan, serta apabila hakim meyakini bahwa peristiwa yang dimaksud benar-benar terjadi. Kualitas dan konsistensi keterangan saksi testimonium de auditu menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kesaksiannya layak dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di pengadilan. Dalam kasus-kasus tertentu yang minim alat bukti, kesaksian testimonium de auditu bahkan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup signifikan.
Baca Juga: Doktrin Marks Rule Sebagai Alat Baca Putusan Pluralitas Mahkamah Konstitusi
6. Saksi mahkota
Istilah saksi mahkota tidak ditemukan dalam KUHAP, namun sering ditemui dalam praktik hukum acara pidana. Istilah saksi mahkota dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”. Sementara menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H., yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.
7. Saksi pelapor (whistleblower)
Saksi pelapor, atau yang dikenal dengan istilah whistleblower, adalah individu yang mengetahui suatu tindak pidana melalui penglihatan, pendengaran, pengalaman langsung, atau keterlibatannya dalam peristiwa tersebut, kemudian melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana itu kepada pihak yang berwenang, seperti penyidik atau penyelidik, untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut. Pada angka 8 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dijelaskan bahwa pelapor tindak pidana atau whistleblower merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
8. Saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator)
Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan. Bantuan tersebut diberikan melalui penyampaian informasi penting kepada aparat penegak hukum serta dengan memberikan kesaksian pada proses persidangan guna memperjelas dan membuktikan keterlibatan pihak-pihak lain dalam tindak pidana tersebut. Istilah justice collaborator dalam konteks hukum Indonesia pertama kali dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang penyusunannya berlandaskan pada Pasal 37 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam praktiknya, SEMA sering berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada angka 9 SEMA No. 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator apabila ia merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam SEMA tersebut. Jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lain yang bersifat terorganisir dan berpotensi mengancam stabilitas serta keamanan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai justice collaborator, yaitu:
- Mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan;
- Tidak berperan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut; dan
- Bersedia memberikan kesaksian di hadapan pengadilan sebagai bagian dari proses peradilan.
Referensi
Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1, (2022): 28
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)
Renie Aryandani, 2024, Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota dan Alibi, Diakses pada tanggal 06 November 2025 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/
Ignatius Ninorey, “Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi a charge dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.Skt)”, Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 3, (2022): 149
Eky Chaimansyah, “Hak Tersangka/Terdakwa untuk Mengajukan Saksi a de charge (Saksi Meringankan) dalam Proses Perkara Pidana”, Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, (2016): 37-39
Jim Robinson, 2023, Expert Witness, Diakses pada tanggal 6 November 2025 melalui https://www.law.cornell.edu/wex/expert_witness
Ridho Asriansyah, 2024, Jenis-jenis Saksi, Diakses pada tanggal 6 November 2025 melalui https://konsultanhukum.id/2024/12/09/jenis-jenis-saksi/
Tim Hukumonline, 2024, Mengenal 8 Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana, Diakses pada 6 November 2025 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=all
Respati Bayu Kristanto & Hervina Puspitosari, “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Pustaka Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby)”, UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 2, (2023): 6656-6658
Admin, 2014, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi, Diakses pada 6 November 2025 melalui https://www.pn-sabang.go.id/?p=1656
Tim Hukumonline, 2024, Mengenal 8 Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana, Diakses pada 6 November 2025 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=all
Nafiatul Munawaroh, 2025, Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator, Diakses pada 6 November 2025 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator-lt58d33e6281239/