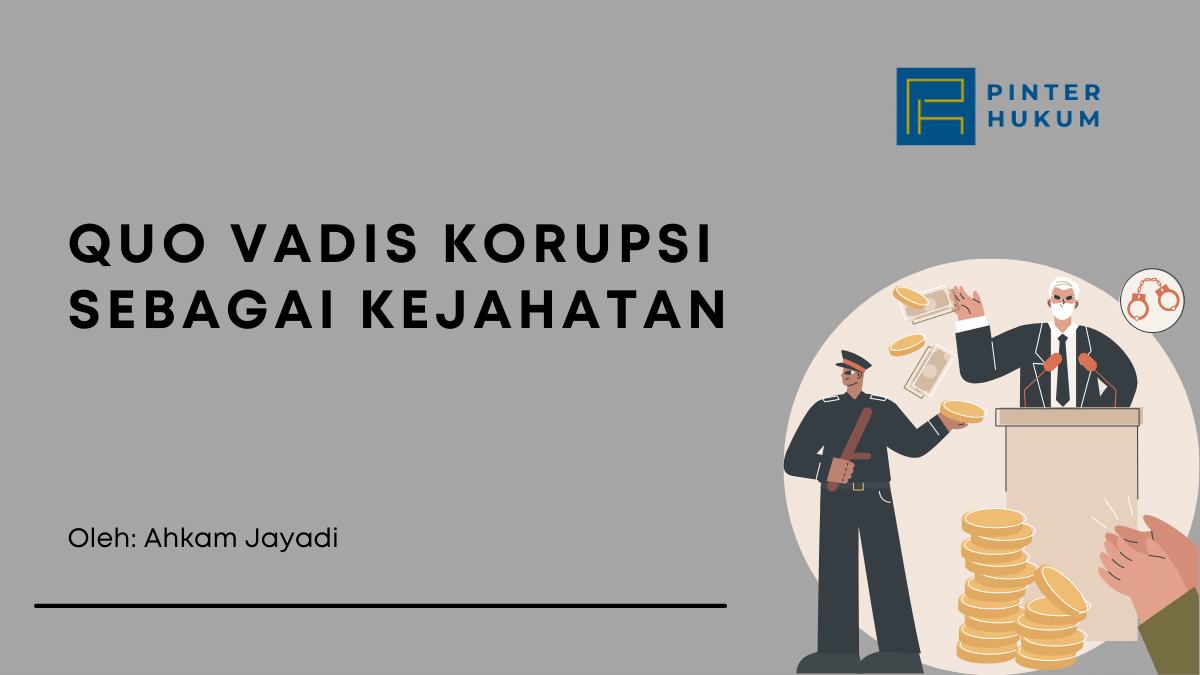Korupsi sepertinya bukan lagi berita yang menyesakkan dada bahkan korupsi itu sendiri sepertinya sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan bangsa ini. Korupsi yang triliunan bisa di SP3 kan. Seorang yang pernah di penjara karena korupsi bisa mendapat penghargaan Doktor (HC) dari sebuah Perguruan Tinggi.
Seorang koruptor yang telah menjalani hukumannya kemudian bisa menjadi Kepala Daerah. Apakah kita sudah tidak memiliki tokoh atau orang-orang yang memiliki latar belakang yang bersih dari segala bentuk kejahatan serta memiliki latar belakang keilmuan yang dapat kita banggakan. Bangsa kita semakin hari semakin aneh saja.
Mungkinkah korupsi sebagai kejahatan akan kita biarkan saja menjadi kebiasaan yang senantiasa akan terjadi dan terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara ini? Beberapa waktu lalu pasca tertangkapnya salah satu hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), maka KPK (di era kepemimpinan Agus Rahardjo) melalui juru bicaranya pada waktu itu Febri Diansyah (Rabu, 14 Maret 2018) mengultimatun para hakim agar tidak ada lagi hakim yang terjaring OTT.
Apa benar ultimatum itu dapat terwujud, sehingga tidak ada lagi hakim atau aparat penegak hukum yang terjerat tindak pidana korupsi. Apakah cukup dengan ultimatum maka tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan terjadi lagi. Bukankah sesuatu yang mengagetkan, meskipun bagi penulis sejatinya tidak perlu kita kaget dengan tertangkapnya lagi penyidik KPK yang memeras Walikota Tanjungbalai (April 2021).
Baca juga:
Pandangan Satjipto Rahardjo Terhadap Pelompatan Tahapan di Masa Reformasi
Dalam sebuah Seminar (Tahun 2019) tentang Korupsi dengan salah satu pembicara adalah komisioner KPK Bapak Laode Muhammad Syarif dan kebetulan penulis sebagai moderator. Salah satu kesimpulan seminar tersebut adalah bahwa: penyebab terjadinya korupsi adalah, “karena ketidak-jujuran”. Apakah benar kejujuran atau ketidak jujuran itulah yang menjadi penyebab terjadinya atau tidak terjadinya korupsi?
Bagi penulis penangkapan terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya tidak akan berhenti. Aparat penegak hukum yang melanggar sumpah jabatannya akan senantiasa terjadi entah sampai kapan. Demikian juga dengan ketidak-jujuran sebagai kambing hitam. Bagaimana sejatinya kita memahami kejujuran atau ketidak-jujuran itu sebagai penyebab terjadi atau tidak terjadinya korupsi?
Betapa tidak dengan bersandar kepada peraturan perudang-undangan yang ada ditambah lagi kode etik yang ada, sumpah jabatan saat dilantik menjadi dan yang paling penting adalah nilai-nilai agama yang mereka anut maka tentu saja tidak masuk di akal kita jika tindak pidana korupsi itu masih terjadi.
Pada tataran inilah kita bisa melihat dan belajar bahwa penyalahgunaan jabatan bukanlah persoalan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan semata. Persoalan pelanggaran kode etik dan yang lainnya akan tetapi ini persoalan hakekat diri. Entitas diri yang hingga kini tidak dipahami wujud dan eksistensinya yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum atau penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan.
Pada ranah inilah penulis menempatkan tindak pidana korupsi itu sebagai kejahatan kemanusiaan. Korupsi terjadi karena manusia itu pada esensinya makhluk yang jahat.
Dari sudut pandang entitas diri maka seseorang terdorong untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum (tindak pidana) disebabkan oleh adanya dorongan hawa nafsu. Entitas hawa nafsu ini tidak akan ada henti-hentinya bergejolak di dalam diri kita. Hawa nafsu tidak akan ada puas-puasnya.
Baca juga: Korupsi Kehendak Tuhan
Pada hawa nafsu inilah entitas kejujuran atau ketidak-jujuran melekat. Setelah punya rumah satu maka hawa nafsu akan senantiasa menggoda pendirian seseorang akan berusaha mempunyai rumah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Demikian juga setelah punya mobil satu maka akan terus diusahakan agar memiliki lagi mobil kedua, ketiga dan seterusnya.
Termasuk juga dengan jumlah uang yang ada di rekening meski pun isinya sudah milyaran maka hawa nafsu akan senantiasa menuntut agar di tambah lagi terus menerus tiada henti. Celakanya apa pun dilakukan demi memenuhi hawa nafsu tersebut termasuk dengan korupsi. Pada tataran inilah persoalan utama dan menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kejahatan karena dorongan hawa nafsu.
Kejujuran dan ketidak-jujuran adalah kesadaran diri untuk merasakan bisikan hati (vpice of the heart) yang ada ketika muncul keinginan untuk menuruti bisikan hawa nafsu untuk melakukan sebuah kejahatan. Kejujuran sejatinya adalah sifat internal yang ditujukan untuk diri kita sendiri, apakah kita masih menyadari betul kalau bisikan jahat itu adalah bisikan setan yang tidak sepantasnya kita turuti.
Sebaliknya ketidak-jujuran adalah ketika kita mengikuti bisikan jahat itu yang kemudian menjelma menjadi perbuatan jahat (perbuatan yang melanggar hukum).
Pada ranah inilah kejujuran dan ketidak-jujuran menjadi tidak berdaya. Kejujuran adalah sifat dasar pendirian manusia, sehingga ketika seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan maka nilai itu pasti muncul dan menegur dalam bentuk rasa, namun sayangnya kebenaran itu tidak berdaya dan terkalahkan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Sayangnya wujud hawa nafsu tersebut kita tidak pahami entitasnya.
Kejujuran, ketidak-jujuran, hawa nafsu harus kita kenali dengan baik bahwa wujudnya adalah dalam bentuk “rasa”. Rasa itu berbicara kepada kita meskipun tanpa suara dan huruf. Rasa inilah yang menjadi persoalan mendasar dari kemanusiaan kita yang tidak pernah kita pahami dan sadari dengan baik.
Kebanyakan kita hawa nafsu hanya dipahami sebagai sebuah konsep, terminologi atau istilah. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyamakan kata hawa dengan nafsu yang kemudian diartikan atau didefinisikan sebagai, “desakan hati dan keinginan keras (untuk menurutkan hati, melepaskan marah, dsb).
Mana wujudnya hawa nafsu itu pada diri kita, bagaimana hawa nafsu itu bisa muncul dalam diri kita dan bagaimana caranya agar hawa nafsu itu tidak muncul pada diri kita? Hal-hal inilah yang selama ini kita tidak pahami sehingga pejabat-pejabat publik dan aparat penegak hukum tiada hentinya melakukan berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana.
Pada sisi inilah sebagaimana penulis kemukakan di atas ultimatum KPK kepada para hakim dan pejabat-pejabat publik tidak akan bermakna. Pelaku korupsi lainnya akan senantiasa bermunculan silih berganti mewarnai pemberitaan media dari hari kehari.
Hawa nafsu adalah entitas diri yang lahir dan terbentuk dari proses kejadian diri kita yang berasal dari empat anasir. Dengan demikian hawa nafsu sejatinya adalah sejenis makhluk Tuhan di dalam diri kita. Wujudnya sebenarnya setiap saat dapat kita rasakan dalam bentuk bisikan hati. Bisikan untuk melakukan kejahatan.
Contohnya ketika kita sendiri di dalam sebuah ruangan dan di atas meja kita lihat ada HP yang tertinggal, maka apa kata hawa nafsu kita, pasti kita bisa rasakan wujudnya, “ambil itu HP lumayan gratis kan tidak ada yang lihat”. Ketika hawa nafsu itu kita perturutkan maka jadilah kita pencuri.
Baca juga: Analisis Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Hawa nafsu itu tidak bisa atau tidak mampu kita lawan karena wujud dan entitasnya adalah makhluk Tuhan. Untuk melawannya maka kita harus meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta atau pemilik entitas tersebut. Wujudnya bagaimana, maka ketika muncul hawa nafsu itu dalam berbagai bentuknya, maka segeralah meminta tolong dengan cara berhakekat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hawa nafsu tersebut tidak mencelakakan kita.
Persoalan berikutnya kebanyakan kita tidak tahu bagaimana cara meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana tempat kita meminta tolong dan kepada Tuhan? Pada tataran inilah kita harus paham dengan sebenar-benarnya paham tentang hakekat diri kita, hakekat Tuhan. Bila ini tidak duduk dengan benar maka lagi-lagi penulis tegaskan ultimatum KPK kepada aparat penegak hukum hanya lah ucapan kosong yang tidak akan bermakna secara substansial.
Demikian juga sekarang ini banyak di antara kita yang telah tidak sadar menjadikan Sains dan teknologi sebagai Tuhannya dengan mensejajarkannya dengan agama. Hal ini terlihat pada saat kita menjadikan sains dan teknologi sebagai sumber nilai untuk mengatur dan menyelamatkan manusia (termasuk sistem nilai atau etika yang diciptakan manusia). Sejatinya sains dan teknologi tidak ada satu pun baik dari disiplin mana pun yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia.
Termasuk di dalam mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.
Oleh sebab itu tingkat pendidikan seseorang tidak lah berbanding lurus dengan sikap dan perilaku jahat. Kenapa sains tidak bisa menyelamatkan kehidupan? Oleh karena yang mau diselamatkan adalah yang datang daripada Tuhan (Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajiun), jelas sains dan teknologi termasuk filsafat tidak punya ajaran untuk menyelamatkannya. Hanya agama yang punya ajaran dan nilai-nilai untuk menyelamatkannya.
Pada tataran inilah tidak ada alasan untuk membatasi keterlibatan agama pada seluruh aspek kehidupan, baik dalam spektrum kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara. Pembatasan keterlibatan agama dalam kehidupan yang disebabkan karena pemahaman yang tidak substantif itulah yang menjadi sumber utama penyebab terjadinya berbagai bentuk kejahatan.
Agama sejatinya mengatur dan mengurus personal yang akan menjadi pejabat negara atau pejabat publik. Seseorang yang akan duduk sebagai pejabat negara atau pejabat publik (baik di lingkungan legislatif, eksekutif terlebih lagi di institusi yudikatif).
Personal-personal tersebut haruslah duduk sebagai personal yang benar sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Jangan sama sekali terjadi seseorang belum selesai pemahaman agamanya secara benar kemudian tampil sebagai pejabat negara atau pejabat publik.
Agama tidak mengurus negara oleh karena personal itulah yang mengurus dan menjalankan negara sebagai amanah masyarakat dan terlebih lagi sebagai amanah Tuhan. Demikian semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menemukan kebenaran sesungguhnya.
Ahkam Jayadi Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar